Malaria yang Membutakan Mataku
Aku (S) dilahirkan di Muntilan, Jawa Tengah, tahun 1943. Diriku tumbuh secara normal seperti anak-anak lainnya yang hidup di lingkungan sekitar rumah orang tuaku. Saat itu, ayahku bekerja sebagai seorang pekerja di bidang kesehatan. Ibu kandungku telah meninggal dunia saat aku berusia 6 tahun. Beberapa saat setelah ibu meninggal dunia, ayah dialihtugaskan ke Makasar. Jadi, aku pun ikut pindah juga bersama ayah. Dalam perjalanan kepindahan dari Muntilan ke Makasar ini, kami naik kapal barang. Di tengah perjalanan di atas kapal inilah aku jatuh sakit. Suhu badanku meninggi. Begitu parahnya sakitku, sehingga makanan dan minuman apa saja yang diberikan kepadaku selalu aku muntahkan. Sebagai seorang petugas kesehatan, dengan segala daya dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ayah berusaha mengatasi penyakit yang kuderita ini. Rupa-rupanya segala upaya yang dilakukan ayah hanyalah menunda malapetaka yang lebih besar yang akan menimpa diriku di kemudian hari.
Kapal yang kami tumpangi ternyata terlambat tiba di pelabuhan, dan tidak bisa dengan segera berlabuh ke pantai. Seluruh penumpang harus menunggu hingga matahari terbit keesokan harinya. Dengan demikian, pertolongan yang seharusnya segera diberikan kepadaku pun jelas kian terlambat. Ditambah pula begitu masuk ke rumah sakit di Makasar, pertolongan yang diberikan pihak rumah sakit hanya berupa suntikan sebagai penurun panas. Aku harus segera diopname untuk menunggu kedatangan dokter yang saat itu sedang bertugas keluar, yaitu melakukan pengobatan keliling daerah yang bisa memakan waktu berhari-hari. Maklumlah, keadaan saat itu sedang berada dalam masa peralihan dari zaman pendudukan Jepang -- Belanda dan Sekutu ke zaman Indonesia yang waktu itu baru saja merdeka dan menjadi negara Republik. Masa itu dikenal juga dengan zaman koalisi.
Ayahku tentu saja menjadi bingung. Sementara itu, panggilan tugasnya sebagai pekerja kesehatan menunggunya di Majene, sebuah daerah yang terletak di luar kota Makasar yang jaraknya cukup lumayan jauhnya dari Makasar. Maklumlah, pada masa itu yang namanya petugas kesehatan amat sedikit jumlahnya, terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Apa hendak dikata, walau semuanya dalam kondisi yang serba kritis, ayah pun dengan sangat terpaksa dan berat hati mesti meninggalkan diriku yang sedang terbaring diopname di Rumah Sakit Umum Makasar. Memang, ayah harus dapat mengutamakan kepentingan umum yang menjadi panggilan tugasnya saat itu, sekalipun harus mengorbankan kepentingan keluarganya sendiri. Ayah lalu berangkat ke Majene, dengan permintaan bahwa keadaan diriku akan terus diberitakan kepadanya secara teratur.
Walau dirawat di rumah sakit, kesehatanku tetap kurang begitu menggembirakan. Suhu badanku tetap tinggi. Dari kedua mataku kini keluar air, sehingga pandanganku berubah menjadi agak kabur. Akibat kondisiku yang tak pernah membaik, hati ayah menjadi tak tenteram. Atas kebijaksanaan atasannya, ayah pun lalu dialihtugaskan ke Rumah Sakit Umum Makasar, dengan tujuan agar dapat langsung ikut terlibat mengurus diriku, yang menjadi anak tunggalnya. Dari keterangan yang berhasil didapatkan, ternyata penyakit malarialah yang menyebabkan panas tubuhku tak kunjung turun, bahkan cenderung meninggi terus. Waktu itu memang cukup banyak berjangkit penyakit malaria tropikana. Pada saat itu penyakit tersebut amat ditakuti semua orang. Penyakit yang kuderita ini kemudian mulai menyerang saraf, sehingga aku memerlukan suatu pengobatan serta perawatan yang cukup lama dan serius.
Dari hasil pemeriksaan, kami mendapat keterangan bahwa saraf mataku terganggu akibat panas yang tinggi dan sudah cukup lama kuderita selama ini. Tak ada pilihan lain. Ayah dan aku harus menerima kenyataan tersebut dengan hati tabah. Beberapa bulan kemudian, kesehatanku pun membaik. Suhu badanku berangsur-angsur turun sampai ke keadaan normal. Akhirnya, aku bisa turun dari tempat tidur dan kondisi tubuhku kembali sehat. Kecuali satu, mataku tetap berair. Hal ini membuat diriku tak tahan bila terkena sinar terang. Memasuki bulan keenam di rumah sakit, saat aku hendak membuka jendela kamarku pada suatu pagi, tiba-tiba saja aku merasa terkejut sekali. Mataku terasa perih seperti disengat api ketika terkena sinar matahari. Kepalaku terasa begitu sakit sekali bagai ditusuk dengan ribuan jarum. Pandangan mataku terasa sangat kabur.
Aku sepertinya berada di dalam lingkungan kabut yang amat tebal sekali. Aku undur dan duduk di tepi ranjangku, sambil merenungi nasib dan memikirkan keadaan diriku. Keadaanku yang seperti itu lalu kuceritakan kepada ayah ketika ia menjengukku pada sore harinya. Dari hasil pemeriksaan dokter, kami mendapat keterangan bahwa saraf mataku terganggu akibat penyakit panas yang tinggi dan cukup lama yang kuderita selama ini. Hal ini mengakibatkan pula terganggunya saraf pada kornea dan selaput mataku.
Pada waktu itu di kota Makasar belum ada tenaga ahli spesialis mata, yang ada hanya di Pulau Jawa. Kami pun lalu dianjurkan untuk segera berobat ke dokter ahli mata yang ada di Pulau Jawa. Namun, karena keadaan yang kurang memungkinkan, ayah baru bisa membawaku ke Pulau Jawa pada tahun 1951. Kepergian itupun sehubungan dengan kepindahan posnya di Bogor. Saat itu kondisiku sudah benar-benar sehat. Hanya saja aku harus selalu mengenakan kacamata hitam guna menjaga mataku yang selalu berair dan tak kuat bila terkena sinar terang. Terutama sekali pada waktu siang hari.
Di Bogor penyakit yang kuderita tidak langsung diobati karena dokter spesialis mata yang ada kebanyakan sedang melakukan tugas keliling ke berbagai daerah. Selama menunggu kedatangan dokter ahli mata, aku menjadi penunggu rumah sambil mengurus ayah yang tetap hidup menduda. Setelah 5 bulan, barulah dokter ahli mata itu dapat menangani penyakit yang kuderita. Dari hasil pemeriksaan intensif yang dilakukannya selama 1 minggu, kami mendapat keterangan bahwa saraf yang menghubungkan mata dan otakku sedang mengalami proses kerusakan yang cukup fatal. Keadaan ini terjadi karena penyakit yang kuderita tidak segera ditangani, dan dibiarkan begitu saja dalam waktu yang terlalu lama. Akibatnya, kondisi yang telah sangat parah ini sulit sekali untuk disembuhkan. "Dalam waktu yang tidak lama lagi, anak Anda akan mengalami kebutaan total!" kata dokter ahli mata itu kepada ayah.
Kebutaan Bukanlah Penghalang untuk Maju
Berita yang didengar dari dokter itu benar-benar memukul hati ayah. Ia menyesali dirinya karena telah mengajakku pindah ke Makasar. Seandainya saja ia tak membawaku pindah dan kalaupun aku sakit, toh masih berada di Pulau Jawa, sehingga tentu keadaanku akan segera bisa diatasi secepatnya. Ia juga menyesali dirinya yang tak memiliki uang cukup banyak untuk membawa diriku sesegera mungkin ke Jakarta saat itu. Sebagai seorang ayah, ia tak bisa memaafkan dirinya atas apa yang terjadi dengan diriku, anaknya. Apalagi ia merasa sebagai seorang petugas kesehatan yang cukup dipandang masyarakat dan sebagai tumpuan harapan kesembuhan atas penyakit yang kuderita.
Sebagai anak kecil yang belum bersekolah, aku menyadari bahwa diriku tidak mungkin hidup sebagaimana anak-anak lainnya. Tetapi, keinginanku untuk bersekolah tetap membara. Lalu aku mendesak ayah agar mengirimku ke sekolah. Ayah menyadari akan kebutuhanku dan dengan segala daya, ia lalu mencari keterangan tentang sekolah yang kudambakan. Dengan segala daya ia mencari keterangan ke sana kemari mengenai sekolah yang bisa menerima diriku dengan kondisi yang kualami. Maka, aku pun kemudian dikirim ke kota Temanggung di Jawa Tengah untuk bersekolah. Aku dimasukkan ke sekolah khusus bagi para tunanetra, yaitu di Sekolah Rakyat Perawatan untuk Anak-Anak Buta.
Di sekolah ini aku dan teman-temanku mendapat pelajaran secara khusus. Semua murid dilatih untuk menggunakan indera pendengaran secara lebih tajam dan lebih teliti, di samping melatih ketajaman daya ingatan yang dimiliki. Semua mata pelajaran yang diberikan tidak jauh berbeda dengan mata pelajaran yang diberikan di Sekolah Rakyat untuk anak-anak normal lainnya. Hanya bedanya di sekolah ini kami belajar menulis, membaca, berhitung dan mendapat bahan bacaan semuanya dengan huruf braille. Di samping memperoleh bahan mata pelajaran biasa, kami juga mendapat mata pelajaran berbagai keterampilan khusus, seperti membuat meja, kursi, bingkai gambar hiasan dinding, menjahit dan menyulam yang tentunya diberikan khusus bagi anak perempuan. Di sekolah ini aku juga mendapat pendidikan rohani. Semua murid yang belajar di sekolah ini tinggal di asrama. Jadi, sebulan sekali ayah menyempatkan diri untuk menengokku di asrama.
Tidak terasa, 6 tahun pun berlalu sudah. Tingkat pendidikan di sekolah itu dapat aku lalui dengan baik. Ini berarti aku harus meninggalkan segala kehangatan yang ada di asrama sekolah itu. Aku kembali berkumpul dengan ayah, yang saat itu secara kebetulan dipindahkan ke Magelang. Kembali aku menjadi penunggu rumah, tanpa memiliki kegiatan yang berarti. Ini membuat sedih hati ayah, karena aku kini kesepian. Pada suatu kesempatan liburan panjang, aku mengundang keponakanku, M, untuk menemaniku di Magelang. Selama masa liburan tersebut, kami banyak melakukan kegiatan bersama -- memasak, berbelanja, membersihkan rumah, bercocok tanam, atau berdiskusi tentang berbagai pelajaran di sekolah. Saat liburan sekolah hampir usai, aku mengantar M ke terminal bis. Dalam perjalanan mengantar itulah, aku mengutarakan keinginanku untuk dapat melanjutkan sekolah. Aku ingin sekali bisa masuk SGB (Sekolah Guru Bawah) agar dapat menjadi guru di kelak kemudian hari.
Mendengar keinginanku tersebut dari M, ayah amat terkejut sekali. Karena dorongan cintanya yang amat besar sekali kepadaku, ayah lalu berangkat ke Salatiga untuk mencari keterangan. Di SGB Kristen, ayah menemui kepala sekolah dan membicarakan tentang keinginanku. Kepala sekolah tersebut setuju menerimaku bersekolah di SGB Kristen asuhannya, dengan suatu tujuan: diriku akan dijadikan objek penelitian SGB tersebut dalam rangka pengembangan pendidikan khusus bagi anak-anak tunanetra. Tahun 1956 aku secara resmi diterima sebagai murid di SGB Kristen Salatiga.
Lima Talenta
Di SGB Kristen Salatiga ini, selain mendapat pelajaran dalam bidang dunia pendidikan, aku juga mendapat pelajaran kerohanian. Di sekolah inilah aku mendengar sebuah khotbah yang amat mengesankan dan menarik hatiku. Khotbah tersebut lalu menjadi bahan pemikiran dan perenunganku, yang pada akhirnya juga mengubah jalan hidupku secara total di kemudian hari. Aku amat terkesan sekali dengan khotbah yang mengambil perumpamaan tentang talenta dengan 3 orang hamba yang diambil dari Injil Matius 25:14-30.
Setelah mendengar khotbah tersebut, timbul keyakinan dan iman yang kuat dalam diriku bahwa setiap orang percaya telah diberi talenta yang sama oleh Tuhan. Bukankah Tuhan adalah Pencipta yang Maha Adil? Tinggal masalahnya sekarang, bagaimanakah cara setiap orang percaya mengembangkan talenta yang sudah diperolehnya. Cara belajarku di SGB Kristen Salatiga memang tidak sama dengan murid-murid lainnya. Aku harus sering ditolong, seperti halnya saat membuat catatan di papan tulis, pada waktu menerangkan mata pelajaran. Buku cetak yang harus aku baca, semuanya tidak ditulis dalam huruf braille. Jadi, teman-temanku menolong membacakan buku itu yang kemudian harus aku salin ke dalam huruf braille. Sesudah itu, aku mesti mengetiknya kembali dengan rapi.
Saat ulangan di sekolah tiba, aku mengerjakannya secara khusus di ruang kepala sekolah. Keistimewaan yang kuterima ini dianggap sebagai hal yang wajar oleh teman-temanku. Di SGB Kristen ini aku pun berhasil lulus dengan memperoleh prestasi yang sangat gemilang. Sebagai penghargaan, aku ditawari untuk masuk SGA (Sekolah Guru Atas) Kristen Salatiga dengan mendapat beasiswa bantuan dari gereja. Kesempatan itu tentu saja tak pernah kusia-siakan. Aku berhasil menyelesaikan pendidikan di SGA tersebut pada tahun 1960.
Setahun kemudian, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) saat itu, Prof. Dr. O. Notohamijoyo, menawariku untuk kuliah di UKSW dengan persyaratan bahwa aku harus lulus ujian masuk. Kesempatan itu pun tak kusia-siakan. Tawaran simpatik tersebut kusambut dengan baik dan penuh semangat. Keadaan fisikku tak menyebabkan diriku menjadi rendah diri. Dengan usaha yang keras dan pantang menyerah, setiap malam aku belajar dengan tekun dan penuh semangat. Hasilnya, aku lulus ujian masuk dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Pendidikan. Di bangku perguruan tinggi inipun aku selalu belajar dengan tekun dan penuh semangat. Kebutaan yang menimpaku bukan merupakan hambatan bagi diriku untuk terus melangkah maju meraih cita-cita pada setiap kesempatan yang diberikan kepadaku. Kekurangan atau cacat fisik yang kumiliki ini, justru menjadi pemacu semangatku untuk belajar secara lebih tekun agar jangan sampai ketinggalan.
Mengembangkan Talenta
Ada banyak mahasiswa asing yang berkunjung di UKSW Salatiga. Mereka ada yang datang dari Jepang, Australia, Inggris, dan juga Amerika. Mereka melihat bagaimana para mahasiswa di UKSW berjuang dengan uletnya, menyalin catatan kuliah atau membuat rangkuman berbagai literatur. Pada saat mereka kembali ke negara asal masing-masing, ternyata nama dan alamatku diberikan ke perpustakaan orang tunanetra. Mereka juga menceritakan tentang kisah perjalanan hidupku ini. Kemudian, aku pun mendapat kiriman berbagai literatur dari "Royal National Institute for the Blind" di London dan dari "Christelijke Bleiden Bibliotheek" di Belanda.
Aku baru tahu kemudian bahwa semangat belajar yang kumiliki dan gairah hidupku yang tinggi untuk mengalahkan berbagai hambatan fisikku selama ini, ternyata membuat para mahasiswa asing itu sangat terkesan. Pada tahun 1965, aku mendapat undangan dari seorang mahasiswa Jepang, untuk datang mengunjungi universitas di Tokyo, Osaka, Kobe, dan Kyoto selama 2 bulan.
Tahun 1967, aku lulus dari Fakultas Pendidikan UKSW dengan angka yang cukup gemilang. Aku lalu ditawari untuk menjadi tenaga pengajar di kampus almamaterku. Tahun 1969, aku resmi menjadi tenaga pengajar tetap dalam bidang Sejarah Pendidikan, Filsafat Pendidikan, dan Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Dalam hal membagikan ilmu kepada orang lain pun, aku ingin bertindak sebagai seorang hamba yang bijaksana, yaitu hamba yang melipatgandakan talenta pemberian tuannya seperti yang telah kudengar dalam khotbah yang amat mengesankan hatiku dan mengubah jalan hidupku. Aku ingin agar orang yang menerima ilmu yang kuajarkan setiap tahun menjadi berlipat ganda jumlahnya. Aku sangat ingin mengembangkan talenta yang kuperoleh tersebut dengan sebaik-baiknya.
Sama seperti manusia normal pada umumnya, aku pun lalu menikah dengan seorang wanita yang berasal dari kota Magelang. Wanita yang kunikahi pada tahun 1979 itu bernama S. Ia seorang mahasiswi di UKSW yang sering kali mengantarkan aku saat pergi ke kantor ataupun ketika pulang ke rumahku yang terletak di kompleks Kampus UKSW. Cinta di antara kami berdua bertumbuh karena "witing tresno jalaran saking kulino" (sebuah pepatah Jawa yang berarti: "Cinta bertumbuh karena terbiasa saling bertemu", Red.). Dari pernikahan ini, kami dikaruniai 3 orang anak yang sehat jasmani semuanya.
Diambil dan disunting seperlunya dari:
| Judul buku | : | Semua Karena Anugerah-Nya |
| Penulis buku | : | Adhy Asmara |
| Penerbit | : | Yayasan ANDI, Yogyakarta 1996 |
| Halaman | : | 2 -- 14 |

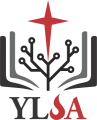

 sabda_ylsa
sabda_ylsa  Yayasan Lembaga SABDA
Yayasan Lembaga SABDA  sabda_ylsa
sabda_ylsa  Selengkapnya
Selengkapnya  SABDA Alkitab
SABDA Alkitab 
 Podcast SABDA
Podcast SABDA  Slideshare SABDA
Slideshare SABDA 